Mampukah Amerika Serikat Memperbaiki Demokrasi Liberalnya Pasca Trump?
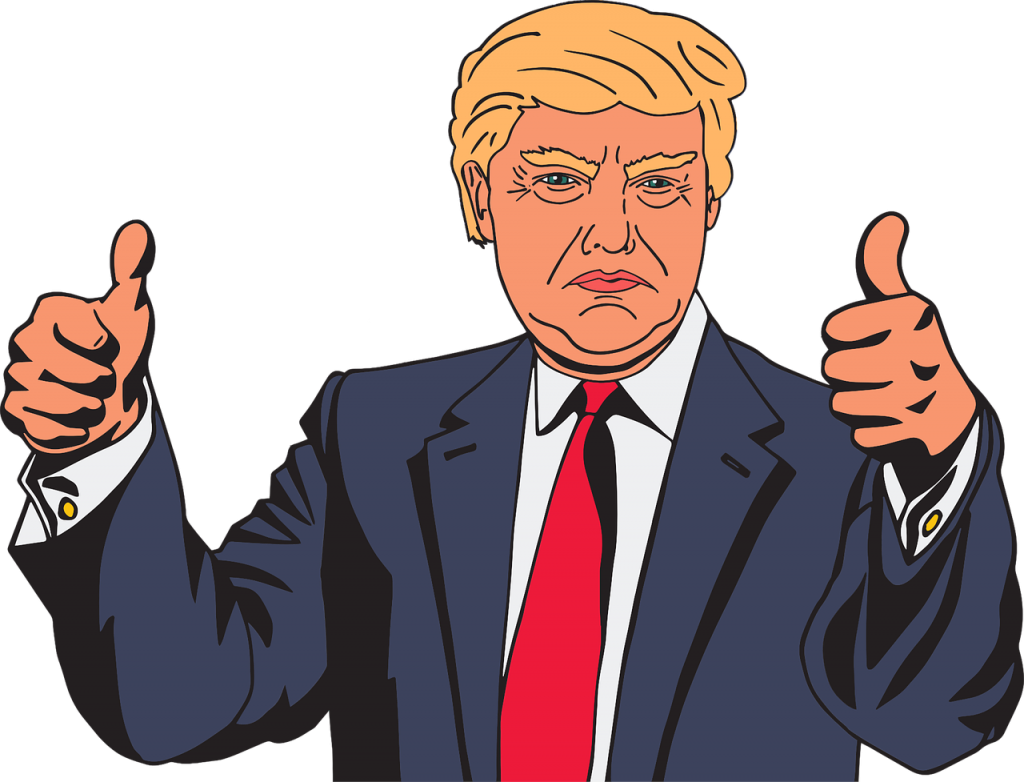
Ilustrasi Donald Trump. Foto: pixabay.com.
Apa yang lebih mengejutkan dari rencana pencalonan Kanye West, seorang rapper berkulit hitam yang dianggap kontroversial atas pendapatnya mengenai perbudakan kulit hitam di masa lalu, pada pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) di bulan November 2020 mendatang? Benarkah Joe Biden serius dalam komitmennya melindungi komunitas muslim Amerika Serikat, atau itu hanya salah satu strategi politiknya dalam menarik pemilih? Lantas, apakah saat ini AS benar-benar dan akan terus mendiseminasi nilai-nilai demokrasi liberal secara optimal?
Dalam memetakan masa depan politik AS tentu penting untuk memperhitungkan kondisi pada status quo, sebab keduanya memiliki korelasi atau bahkan hubungan kausalitas. Oleh karenanya, untuk mengetahui gambaran jalannya pemilu AS 2020 serta ketahanan demokrasi liberal AS ke depannya, masyarakat perlu mencermati lebih lanjut tren pemilu terakhir serta gaya kepemimpinan sang petahana, Donald Trump.
Kemunculan Trump: Ancaman atas Demokrasi Liberal?
Hubungan pasang surut Trump dengan perpolitikan AS telah lama dimulai semenjak ia resmi mencalonkan diri sebagai kandidat presiden AS pada Juni 2015. Dari masa kampanye hingga kemenangannya, Trump memang sering sekali mengejutkan masyarakat global akibat narasi-narasi dalam kampanyenya yang dinilai terlalu kontroversial. Apalagi waktu itu, terdapat prediksi yang menunjukkan kemenangan pasti di tangan Hillary Clinton.
Kepemimpinan Trump pasca resmi menjadi orang terpenting nomor satu di AS pun tak lepas dari kritik yang datang dari oposisi sekaligus masyarakat internasional yang khawatir dengan masa depan politik AS dan nilai-nilai demokrasi secara keseluruhan. Melansir dari survei yang dilakukan oleh Gallup, sebuah perusahaan konsultasi manajemen kinerja global asal AS, di bulan Oktober 2019, sebanyak 34 persen masyarakat AS merasa tidak puas dengan kinerja Trump, utamanya terkait urusan bad governments/poor leadership/politicians yang menempati urutan teratas. Rekor ini hampir menjadi yang tertinggi semenjak Gallup mengadakan polling di tahun 2001 terkait kinerja pemimpin AS (Brenan, 2019). Data tersebut tentu menarik untuk dijadikan bahan acuan dalam mengoreksi kembali etika-etika politik yang ‘salah’ pada pemilu 2016 berdasarkan premis demokrasi liberal, khususnya terkait pendekatan politik yang dipilih Trump sehingga dapat diambil suatu pembelajaran penting dalam menyongsong pemilu yang akan datang.
AS telah sejak lama dikenal sebagai the land of the free yang memegang teguh akar-akar demokrasi liberal. Perbedaan yang jelas dengan demokrasi secara umum terletak pada perlindungan kemerdekaan dan privasi individu atas partisipasi mereka di pemerintahan, serta pembuatan kebijakan yang inklusif (Constant, 1988). Namun, dalam rentang waktu yang lama pula, beberapa politisi telah mempraktekkan pendekatan populisme dalam aktivitas kampanye mereka. Menurut banyak akademisi, pendekatan tersebut sering kali dianggap sebagai bentuk dari illiberal democracy (Galston, 2018), sebab kurang mempertimbangkan suara kelompok rentan.
Populisme esensinya merupakan suatu pendekatan politik yang dilakukan dengan cara menciptakan dikotomi pemikiran antara “the pure people”, atau mereka yang seringkali merasa tertinggal dalam proses globalisasi sehingga menjustifikasi tindakan mengumbar kebencian dan protes guna mereformasi kondisi pada status quo, dengan “the corrupt elite“, atau kelompok yang tergabung dalam suatu institusi demokrasi dan dipandang gagal dalam memfasilitasi suara populer (Molloy, 2018). Pemimpin populis sejati lantas mengklaim diri mereka sebagai perwakilan “kehendak rakyat” yang dipersatukan guna melawan elite korup, yang dianggap sebagai musuh bersama (Molloy, 2018). Bertolak dengan menggunakan kebencian publik ini, lantas pemimpin populis biasanya memilih target yang mudah untuk disalahkan dan hanya menawarkan solusi sederhana bahkan terkadang bersifat tak rasional.
Dalam konteks Trump, ia sering kali mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari kelompok WASPs (White-Anglo-Saxon-Protestan) yang menyusun mayoritas masyarakat AS, atau dikenal sebagai kelompok sayap kanan. Identitas tersebut lantas menjadikan Trump menjustifikasi segala tindakan terkait penyebaran ujaran kebencian kepada kelompok yang menurutnya ‘menang’ di atas globalisasi. Misalnya, Trump yang menuduh kelompok Muslim sebagai dalang atas aksi terorisme dan lantas melarang imigran Muslim untuk masuk ke AS, berangkat dari ketakutan kelompok WASPs atas maraknya terorisme global dan keterulangan persitiwa 9/11 (Gilsinan, 2018).
Belum lagi, Trump yang mempercayai climate change sebagai berita bohong, sambil kemudian menyalahkan the scientist yang dianggap memiliki “agenda politik” lain untuk mengacaukan ekonomi AS. Trump berusaha mengkapitalisasi posisi politik yang beranjak dari kemarahan pekerja tambang yang kehilangan pekerjaan mereka di bawah kepemimpinan Obama, yang cukup progresif terhadap isu lingkungan (BBC, 2018).
Trump juga menyalahkan kelompok migran sebagai pencuri pekerjaan dan pembunuh yang hanya membawa kematian dan kerusakan (Cranley, 2018). Hal ini berangkat dari natives xenophobic yang merasa kehilangan pekerjaan mereka akibat kompetisi asing (Nye, 2020).
Berbagai kebencian tersebut disatukan oleh Trump ke dalam narasi-narasi kampanye yang begitu kontroversial agar keresahan masyarakat dapat ‘terwakili’ dengan representasinya. Konsekuensinya, masyarakat melihat kandidat bersandarkan pada ketakutan atas hilangnya “posisi” mereka di panggung sosial ekonomi, alih-alih menilai dengan kritis program-progam yang ditawarkan.
Masyarakat dapat melihat imbas atas pendekatan ‘menggiring kebencian dan menjual jawaban enteng’ milik Trump tersebut pada tingkat ketidakpuasan publik pada berbagai kebijakannya. Masih mengacu pada polling yang diinisiasi oleh Gallup di tahun yang sama, ditunjukkan bahwa isu-isu seputar imigrasi, ras, dan perubahan iklim mulai menempati 6 masalah terpenting yang dihadapi AS menurut masyarakat domestik, berbeda dengan kepemimpinan Obama, yang membawa ekonomi menjadi isu sentral (Brenan, 2019). Hal ini jelas berhubungan dengan narasi Trump yang menuding kuasa kelompok tertentu serta abai terhadap solusi yang bersifat struktural sehingga melemahkan kualitas pengambilan kebijakan pada institusi demokrasi dan upaya checks and balances.
Mengambil contoh pada kasus pembangunan tembok perbatasan antara AS dan Meksiko yang telah kontroversial sejak awal dan dinilai sebagai slogan populisme Trump. Sebagai balasan atas ketakutan Trump terkait imigran ilegal yang dapat masuk dari Meksiko, penulis dapat melihat adanya pembuatan keputusan yang terpusat di tampuk kekuasaan eksekutif saja. Anggapan ini bertolak dari keputusan semena-sema Trump untuk mengalokasikan dana terkait pembangunan tembok tersebut melalui Pentagon, sekalipun anggota parlemen di kongres secara mutlak menolak adanya pengajuan dana (DW, 2019).
Fenomena ini lantas menunjukkan lemahnya checks and balances antarbadan legislatif dan eksekutif, serta pembuatan keputusan yang semata-mata dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi janji kampanye tanpa mempertimbangkan pertimbangan dari pihak lain, sehingga kualitasnya pun perlu dipertanyakan. Padahal, check and balances dibutuhkan agar pengambilan keputusan didasarkan pada pertimbangan yang cermat sehingga output yang dihasilkan dapat menjangkau secara maksimal, sesuai premis demokrasi liberal. Lebih lanjut, terpusatnya pembuatan keputusan juga dinilai mampu membawa AS ke dalam bentuk kepemimpinan diktator seperti yang terjadi di Turki, Venezuela, dan Thailand (Liddiard, 2019).
Populisme 4.0
Kebobrokan strategi yang dilakukan Trump, sekaligus yang perlu diwaspadai oleh masyarakat terhadap pemilu selanjutnya, adalah pemanipulasian big data pemilih oleh Cambridge Analytica. Waktu itu, tim pemenangan Trump bersama Cambridge Analytica diduga mengarahkan pemilih untuk memilih kandidat dari Partai Republik tersebut dengan menggunakan pendekatan microtargeting dan memanfaatkan strategi psychometric. Melalui Facebook, data pemilih, yang termasuk di dalamnya informasi pribadi, status, dan pengikut, akan dipantau secara ilegal, dianalisis sesuai kondisi psikologis individu, untuk kemudian diarahkan pada narasi-narasi seputar berita palsu, misinformasi, ujaran kebencian, dan agenda politik Trump melalui iklan di Facebook (The Great Hack, 2019).
Satu hal yang berbahaya dari penggunaan strategi ini adalah bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh Cambridge Analytica hanya ditujukan pada individu-individu tertentu saja dan dengan cepat menghilang, sehingga kecil kemungkinan dapat diketahui individu lain atau lebih parahnya, sulit dilacak oleh lembaga berwenang. Penggunaan strategi yang melanggar privasi data pemilih tersebut dinilai oleh penulis sebagai bentuk pencorengan pula terhadap konsep human security yang harusnya dijamin penuh dalam demokrasi liberal. Lebih dari itu, kemampuan Trump untuk mampu mengarahkan atau mengganti preferensi pemilih secara ilegal dan rahasia juga menodai premis utama dalam demokrasi liberal terkait pemilihan umum yang seharusnya berlangsung dengan bebas, sehingga penulis menilai fenomena ini lebih pantas dikaitkan dengan demokrasi terarah dan tidak sepenuhnya bebas dari pihak eksternal. Pernyataan Sam Abrams, profesor ilmu politik di Sarah Lawrence College yang menyebutkan bahwa,
“Microtargeting is one thing, but messaging, if you can tap into the right story at the right time, can be more powerful than that.” (Richardon, 2018).
Hal ini membawa penulis pada suatu kesimpulan bahwa microtargeting ditambah dengan penggunaan strategi populisme mampu menjadi ancaman serius pada lanskap demokrasi AS kedepannya.
Populisme dan strategi microtargeting yang dapat mengarah ke aksi kriminal tampaknya masih akan terus menjadi fenomena yang perlu diwaspadai dalam arena perpolitikan AS di tahun-tahun berikutnya. Menurut Nye, populisme kemungkinan akan terus bersambung di AS selama pekerjaan manusia hilang karena penggunaan robot, yang tidak terbatas hanya di perdagangan saja, dan perubahan budaya akibat globalisasi yang dapat terus memecah belah masyarakat (Nye, 2020). Selagi ekonomi masih menjadi masalah pelik bagi sebagian orang, penulis menilai pemimpin yang populis tidak akan pernah kekurangan bahan untuk dikampanyekan dalam agenda politiknya. Apalagi, dengan situasi pandemi COVID-19 dan keresahan akibat gerakan Black Lives Matter saat ini, dapat menjadi bahan propaganda empuk untuk mengadu domba masyarakat. Dengan begitu, mengulang pertanyaan penulis sendiri di awal, benarkah Kanye West dan Joe Biden serius dalam menawarkan inklusivitas kebijakan sebagai tandingan dari populisme Trump?
Sementara itu, kasus Cambridge Analytica mungkin telah selesai, tapi bukan tidak mungkin akan bertransformasi ke bentuk-bentuk baru mengingat ketidakpopuleran kasus tersebut di mata masyarakat global, serta belum adanya hukum yang meregulasi internet privacy. Perjalanan demokrasi liberal AS boleh dikatakan masih panjang, tapi menurut Rudolph, mantan Direktur Congressional Budget Office, setidaknya populisme dapat direm kecepatannya apabila terdapat reformasi di tingkat legislatif yang selama ini sering dianggap tidak cakap sebagai institusi demokrasi. Walaupun perbaikan tersebut tidak akan serta merta menghilangkan pemimpin yang populis, setidaknya kualitas debat dapat lebih meningkat setelah melalui deliberasi yang lebih cermat (Penner, 2020). Selain itu, diperlukan juga peningkatan kesadaran serta upaya kritis pada masyarakat dalam menilai kualitas calon kandidat saat berlangsungnya kampanye. Masyarakat perlu menaruh perhatian lebih pada evidence-based policy dan mempertanyakan ulang calon yang abai terhadap fakta science.
Alifia Sekar adalah mahasiswa tingkat pertama Ilmu Hubungan Internasional, UGM.
Referensi
BBC. 2018. Trump on climate change report: ‘I don’t believe it’”. Available at: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-46351940
Brenan, M. 2019. Mentions of Government as Top U.S. Problem Near Record High. News Gallup. Available at: https://news.gallup.com/poll/267581/mentions-government-top-problem-near-record-high.aspx
Cranley, E. 2018. Trump says ‘thieves and murderers’ are coming into the US as he responds to outrage over immigration policy. Business Insider Singapore. Available at: https://www.businessinsider.sg/trump-thieves-and-murderers-coming-into-the-us-immigration-2018-6?r=US&IR=T
Constant, B. 1988. The Spirit of Conquest and Usurpation and Their Relation to European Civilization. Benjamin Constant: Political Writings, trans. and ed. Biancamaria Fontana, 102. Cambridge: Cambridge University Press.
DW. 2019. Pentagon approves billions to build Trump’s border wall with Mexico. Available at: https://www.dw.com/en/pentagon-approves-billions-to-build-trumps-border-wall-with-mexico/a-50280132
Galston, W.A. 2018. The Populist Challenge to Liberal Democracy. Journal of Democracy. Available at: https://www.journalofdemocracy.org/articles/the-populist-challenge-to-liberal-democracy/
Gilsinan, K. 2018. Trump Keeps Invoking Terrorism to Get His Border Wall. The Atlantic. Available at: https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/12/trump-incorrectly-links-immigration-terrorism/576358/
Liddiard, P. 2019. Is Populism Really a Problem for Democracy?. Wilson Center. Available at: https://www.wilsoncenter.org/publication/populism-really-problem-for-democracy
Molloy, D. 2018. What is populism, and what does the term actually mean?. BBC. Available at: https://www.bbc.com/news/world-43301423
Nye, J. 2020. Why Is Populism on the Rise and What Do the Populist Want?. The International Economy, 13. Available at: http://www.international-economy.com/TIE_W19_PopulismSymp.pdf
Penner, R.G. 2020. Why Is Populism on the Rise and What Do the Populist Want?. The International Economy, 17. http://www.international-economy.com/TIE_W19_PopulismSymp.pdf
Richardon, D. 2018. What the Cambridge Analytica Revelations Signal for Future Political Campaigns. Observer. Available at: https://observer.com/2018/03/cambridge-analytica-revelations-signal-future-political-campaigns/
The Great Hack. 2019. [film] Directed by K. Amer and J. Noujaim. America: The Others.





